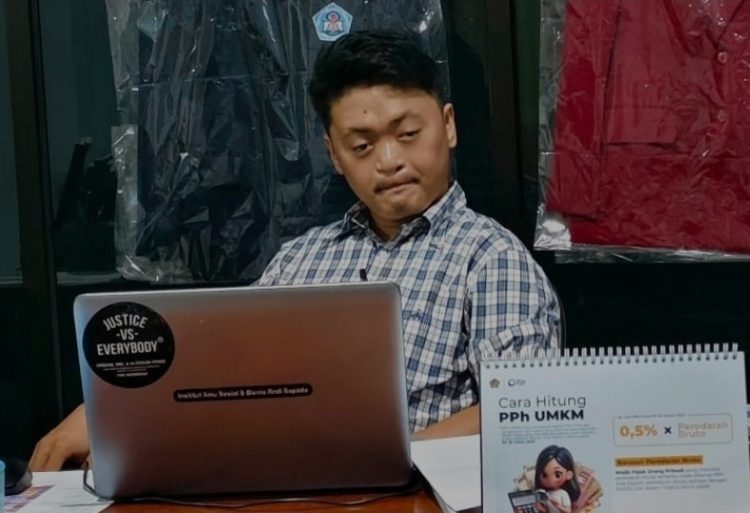Oleh:
Muh. Akbar Fhad Syahril
Dosen Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Kota Parepare
Keberadaan teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia ibarat darah yang mengalir di antara ruang-ruang sosial kita. Setiap hari, hampir setiap orang mulai dari pekerja urban di kota besar hingga petani di desa, memanfaatkan aplikasi telepon berbasis internet seperti WhatsApp Call, Telegram, hingga layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) lain untuk bertukar kabar, berdiskusi, hingga melakukan transaksi bisnis. Digitalisasi ini bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata di era globalisasi. Namun, kini masyarakat dihadapkan pada gagasan “pembatasan fitur telepon” oleh KomDigi merupakan sebuah langkah regulasi yang mengundang pro dan kontra yang cukup sengit.
Rencana pembatasan ini, menurut KomDigi, dilatarbelakangi keinginan untuk menjaga ekosistem bisnis operator telekomunikasi konvensional yang selama ini menopang infrastruktur komunikasi nasional. Pendapatan operator dari layanan SMS dan panggilan suara kian tergerus oleh kehadiran OTT (over-the-top) seperti WhatsApp, yang menawarkan layanan serupa bahkan lebih unggul, secara gratis asalkan tersedia koneksi internet. Inilah alasan utama KomDigi mengajukan wacana pembatasan, dengan harapan mendorong kelestarian bisnis operator dan keberlanjutan investasi infrastruktur.
Di satu sisi, logika yang ditawarkan KomDigi memang masuk akal. Operator menghabiskan investasi besar untuk membangun dan memelihara jaringan, dari menara BTS hingga kabel serat optic, namun justru ‘ditikung’ oleh aplikasi digital yang hanya menumpang pada infrastruktur tersebut. Ketidaksetaraan ini memang menjadi persoalan strategis yang perlu ditangani pemerintah jika ingin ekosistem komunikasi digital tetap sehat dan berkelanjutan. Tidak sedikit negara lain yang juga menghadapi dilema serupa.
Namun, harus diakui bahwa pembatasan fitur telepon berbasis internet bukannya tanpa konsekuensi serius. Kita hidup di era keterbukaan informasi di mana segala sesuatu bergerak serba cepat. Pembatasan semacam ini berisiko membuat kita justru mundur ke belakang, kembali ke era komunikasi yang mahal dan terbatas, di mana biaya menelepon ke luar negeri atau bahkan antarprovinsi saja bisa membuat sebagian warga berpikir dua kali untuk terhubung.
Dari sudut pandang konsumen, tentu saja wacana ini menimbulkan keresahan. Tidak sedikit pelaku UMKM, pekerja migran, mahasiswa, hingga tenaga medis di daerah terpencil yang sangat bergantung pada VoIP untuk menjalankan aktivitasnya. Bayangkan bagaimana repotnya jika untuk menghubungi keluarga di luar negeri, atau melakukan koordinasi lintas kota, harus kembali melalui jalur komunikasi konvensional yang berbiaya tinggi? Bukan hanya ketidakpraktisan, tetapi juga ancaman pada efisiensi, daya saing, dan inklusi sosial.
Lebih jauh, pembatasan fitur telepon cenderung mengabaikan perkembangan pola hidup digital masyarakat saat ini. Cara orang berkomunikasi telah bergeser secara fundamental. Anak muda, misalnya, lebih nyaman melakukan panggilan video ketimbang hanya bertukar SMS. Pelayanan publik pun mulai banyak memanfaatkan komunikasi daring karena efektivitas dan kecepatan yang ditawarkan. Pembatasan jelas akan menciptakan kemacetan komunikasi dalam berbagai lapisan kehidupan.
Pertanyaan besar pun muncul: Apakah langkah pembatasan fitur telepon benar-benar solusi menghadapi tantangan digitalisasi, atau justru bentuk resistensi terhadap perubahan zaman? Jika regulasi diciptakan atas dasar menjaga status quo, sulit untuk membayangkan Indonesia mampu bersaing di ranah ekonomi digital global yang menuntut adaptasi dan inovasi tanpa henti.
Tak bisa dinafikan, pembatasan fitur telepon bisa juga menimbulkan efek bola salju yang membahayakan. Dengan semakin sempitnya akses komunikasi, masyarakat makin rentan mencari jalan alternatif yang kadang tidak legal ataupun tidak terpantau, seperti aplikasi komunikasi gelap yang sulit dikontrol oleh negara. Alih-alih menciptakan ketertiban, pembatasan malah dapat memperbesar permasalahan baru yang tak terduga.
Aspirasi pembatasan juga harus direnungkan dari aspek hak asasi manusia, khususnya hak mendapatkan akses atas informasi dan kebebasan berekspresi. Bukankah negara juga wajib memastikan masyarakat bisa mengakses komunikasi yang cepat, aman, dan terjangkau? Menerapkan larangan atau pembatasan secara masif justru bisa mencederai prinsip demokrasi yang menjunjung kebebasan warga dalam menjalani kehidupan digital.
Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap? Daripada mengambil solusi instan semacam pembatasan, rasanya lebih bijak jika KomDigi mendorong adanya kolaborasi yang sehat antara operator konvensional dan pelaku OTT. Regulasi dapat diarahkan pada upaya pembagian beban infrastrukur atau pembuatan skema kerja sama bisnis, sehingga keberlangsungan industri tetap terjamin tanpa harus mengorbankan kepentingan publik.
Negara-negara maju umumnya memilih jalan dialog dan negosiasi. Misal, Eropa mendorong penyusunan aturan fair share, di mana OTT ikut memberi kontribusi pada operator. Skema seperti ini memungkinkan terciptanya “win-win solution” tanpa harus merampas hak masyarakat dari kemudahan komunikasi digital. Indonesia, sebagai bangsa besar dengan tingkat adopsi teknologi tinggi, seharusnya bisa meneladani cara-cara inovatif ini.
Tugas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak kehilangan kemudahan yang sudah dinikmati berkat digitalisasi. Kehadiran teknologi komunikasi bukan musuh, melainkan harapan bagi kehidupan yang lebih efisien dan terjangkau. Pembatasan bisa dimaknai sebagai kegagalan negara menghadapi tantangan inovasi, dan membahayakan posisi Indonesia dalam peta persaingan ekonomi digital global.
Lebih krusial, penentuan solusi atas persoalan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat. Jangan sampai regulasi lahir di ruang-ruang tertutup tanpa mendengarkan aspirasi warga pengguna layanan. Pendekatan dialogis dan terbuka jauh lebih efektif dibandingkan keputusan sepihak yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
Kuncinya terletak pada keberanian berinovasi dalam regulasi. Pemerintah harus mampu menemukan cara baru dalam mengelola relasi antara bisnis dan kepentingan publik di era digital, bukan sekadar mengambil solusi kuno yang sudah tidak relevan dengan tantangan hari ini. Dukungan infrastruktur, edukasi digital, serta perlindungan konsumen harus menjadi prioritas.
Selain itu, regulasi juga harus memupuk lahirnya kolaborasi antar platform. Operator dapat menggali potensi kemitraan strategis dengan pelaku OTT, misal lewat bundling data, penawaran value-added service, atau pengembangan fitur lokal khusus bagi masyarakat Indonesia. Dengan jalan kolaborasi, semua pihak akan lebih diuntungkan.
Mari kita belajar dari sejarah. Ketika SMS dan telepon konvensional dulu hadir, banyak pihak yang menentangnya karena dianggap akan mengancam tatanan lama. Tapi, justru dari perubahan itulah lahir kemajuan pesat dunia komunikasi. Membatasi fitur telepon di era digital hanya akan mengulangi kesalahan yang sama: menolak inovasi demi melanggengkan zona nyaman.
Pada akhirnya, masa depan komunikasi Indonesia ditentukan oleh seberapa berani kita menghadapi zaman. Apakah kita akan memilih solusi digital yang progresif, atau justru berlama-lama di zona masa lalu mundur ke era lama, menutup pintu untuk kemudahan dan kemajuan? Momen ini menjadi ujian kepiawaian pemerintah dalam mengelola perubahan demi memastikan masa depan komunikasi yang inklusif, efisien, dan adil.
Sudah saatnya pemerintah membuka ruang partisipasi publik, menghadirkan regulasi progresif, dan mengawal agar digitalisasi menjadi berkah, bukan ancaman. Karena sesungguhnya, teknologi adalah alat, dan manusialah yang menentukan arah penggunaannya: untuk maju bersama, atau mundur kembali ke era lampau yang serba terbatas.
Maka dari itu, kalau memang pembatasan fitur telepon jadi diberlakukan, siap-siap saja kita kembali ke zaman di mana nada dering “kring, kring, kring” dari telepon rumah menjadi senjata pamungkas untuk mencari kabar. Barangkali, lempar kode lewat pager atau telegram akan menjadi tren kekinian, sementara generasi muda sibuk googling, “cara menulis surat cinta versi kakek-nenek.” Kalau begini terus, jangan-jangan, sebentar lagi, tukang pos bakal jadi profesi primadona lagi di era digital. Jadi, selamat datang di masa depan dengan sedikit rasa nostalgia era jadul yang dibalut dalih kebijakan!
(***)